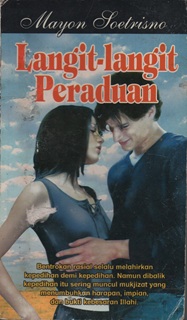Benarkah Demokrasi Sudah Menghantarkan Kita Kepada Kesejahteraan?
Selasa, 3 Desember 2024 18:46 WIB
Demokrasi dan Kesejahteraan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Demokrasi berkembang di negeri ini, namun tidak demikian dengan kesejahteraan.Kenapa?
Merefleksikan Kembali Demokrasi
Saya teringat satu saat kami mahasiswa Magister DPP Fisipol UGM melaksanakan aksi turun ke jalan. Saat itu kami memprotes kebijakan DPR yang hendak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal putusan MK itu dianggap sangat progresif bagi masyarakat karena mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Putusan MK menentang upaya politik praktis untuk memenangkan pilkada pada November 2024 dengan mekanisme kotak kosong. Caranya sederhana, para partai berkumpul dan membuat koalisi super gemuk sehingga calon yang diusung diatur sedemikian rupa agar hanya menghadapi kotak kosong. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan semacam threshold tertentu dalam mengajukan calon.
Putusan MK kemudian membuat threshold ini menjadi lebih mudah (dengan cara menurunkan threshold tersebut) agar semakin banyak calon yang bisa mencalonkan diri meski tidak berada dalam koalisi gemuk. Saat itu, DPR berencana melawan Putusan MK tersebut. Alhasil, publik marah dan aksi turun ke jalan tidak bisa dibendung.
Jelas bahwa rencana partai politik membangun koalisi super gemuk dan berupaya memenangkan pilkada dengan cara kotak kosong tidak sesuai dengan semangat demokrasi, salah satunya menurut Grindle dalam Free Competition.
Aksi massa tersebut berupaya untuk menyelamatkan dan menegakkan demokrasi. Di UGM kami dikoordinir berbagai pihak, sehingga memang massa pada waktu itu sangat banyak dan tentu saja tidak hanya oleh mahasiswa UGM. Namun saat mengikuti aksi massa tersebut, saya cukup tercengang ketika kami melaksanakan long march ke titik nol Jogja melewati jalan Malioboro. Salah satu yang cukup mencengangkan bagi saya yaitu ketika saya melihat seorang ibu ditengah kerumunan massa yang sangat banyak justru sibuk mengais sampah dari tempat sampah di sekitaran Malioboro.
Kejadian ini pun membawa refleksi pribadi ke saya dengan memunculkan berbagai pertanyaan dalam benak. Apa bagi ibu ini demokrasi yang sedang dihancurkan bukan sesuatu yang patut dibela dan penting bagi dia juga? Apakah sampah itu lebih berharga ketimbang mempertahankan demokrasi yang diraih dengan darah pada Tahun 1998? Apa dia menyadari tentang pentingnya demokrasi? Apakah ibu itu menyadari aksi kami atau tidak?
Rupa-rupanya memang dalam konteks Indonesia dimana demokrasi masih berkembang, kesadaran berdemokrasi tidak hanya bagi elit tetapi juga bagi masyarakat umum masih minim. Studi mengenai politik uang dari Burhanuddin Muhtadi misalnya, dalam setiap pelaksanaan pemilihan selalu menjadi masalah klasik. Politik uang menandakan ketidakdewasaan politik dan sekaligus menghambat praktik demokratisasi di Indonesia.
Namun, politik uang kian subur menggerogoti demokrasi bagi masyarakat karena kegagalan negara menghasilkan produk kebijakan yang berbasis kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk mencari kesejahteraan lewat cara-cara informal. Oleh karena itu perlu untuk memikirkan kembali bagaimana sebenarnya relasi antara demokrasi dan kesejahteraan terjalin. Hasil penelitian antara PolGov UGM dan Universitas Oslo, Norwegia dengan tajuk “The Politics of Welfare: Contested Welfare Regimes in Indonesia” bagi saya menarik untuk melihat relasi antara demokrasi dan kesejahteraan.
Relasi Demokrasi dan Ekonomi
Dalam studi politik dan ekonomi, Adam Przeworski et.al, berpendapat bahwa pendapatan per kapita menjadi syarat mutlak berlakunya demokrasi yang baik. Adam Przeworski dan Fernando Limongi mengkaji setiap negara di dunia antara tahun 1950 dan 1990, temuan mereka ialah negara demokratis dengan pendapatan dibawah 1.500 dollar hanya akan bertahan selama delapan tahun. Sedangkan negara dengan pendapatan 1.500-3.000 dollar akan terus bertahan sekitar delapan belas tahun. Ada pun negara dengan pendapatan sebesar 6.000 dollar atau lebih akan menjadi sangat kuat.
Kesimpulan Przeworski dan Limongi ialah dengan pendapatan sebesar 3.000-6.000 dollar proses demokratisasi akan cenderung bertahan dan berhasil. Hal ini didukung pula oleh Seymour Martin Lipset yang pernah mengemukakan bahwa semakin makmur suatu bangsa, semakin besar kesempatannya mempertahankan demokrasinya. Agak berbeda dengan sebelumnya, peraih Nobel tahun 2024 Daron Acemoglu bersama rekan-rekannya pernah melakukan sebuah studi, dimana dalam studinya demokrasi ternyata dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar 20 persen dalam jangka waktu yang panjang.
Perbedaan gagasan antara Acemoglu dan Przeworski terletak pada kondisi apa yang seharusnya didahulukan. Dalam studinya Przeworski keadaan ekonomi menjadi prasyarat berlakunya demokrasi yang baik, sebaliknya menurut Acemoglu, demokrasi menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun demikian terlepas dari pertanyaan tersebut intinya aspek demokrasi kesejahteraan seharusnya menjadi gagasan yang perlu digagas kedepan.
Demokrasi seharusnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun demikian tidak mungkin menghadirkan demokrasi kesejahteraan bila misalnya suatu rezim demokrasi semakin diikat dengan kekuatan oligarki yang semakin menguat yang ditandai dengan semakin tingginya ketimpangan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah ataupun tidak mungkin melaksanakan demokrasi kesejahteraan bila fungsi representasi politik semakin melemah, yang ditandai kegagalan bekerjanya lembaga representasi rakyat (misalnya DPR) dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Laporan Celios terbaru (2024) mendapati bahwa sejak 2020 (Pasca Covid-19) ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Serupa dengan itu, Wawan Mas’udi, Cornelis Lay dan Hasrul Hanif dengan mengutip beberapa laporan misalnya OXFAM (2017) dan World Bank (2014) mendapati bahwa kekayaan empat orang di Indonesia setara dengan kekayaan lebih dari 100 juta orang miskin, selain itu selama kurun waktu 15 tahun World Bank mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami ketimpangan tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Dalam temuan Project Power, Welfare, Democracy (PWD) Fisipol UGM, kebutuhan akan kesejahteraan hidup oleh masyarakat mengakibatkan proyek-proyek kesejahteraan kerap kali menjadi narasi populis. Pada saat yang bersamaan juga turut menghadirkan pemimpin populis dan kebijakan populis pula yang kadangkala tidak realistis dan tentu saja kadangkala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kebijakan kesejahteraan akhirnya menjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sebagai contoh disalah satu provinsi di Pulau Sulawesi, meski ada program beasiswa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun menyediakan hal yang sama. Akibatnya, kadangkala distribusi penyalurannya menjadi tumpang tindih dan tidak sedikit justru masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebijakan tersebut adalah masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tertentu atau diberikan hanya kepada mereka yang berjasa dalam memenangkan calon kepala daerah.
Alhasil meski demokrasi prosedural telah berjalan cukup baik atau setidaknya lebih baik ketimbang di era Orde Baru sehingga mampu membawa kestabilan justru dalam temuan PWD menemukan bahwa prosedur dan lembaga demokrasi yang stabil dan baik di Indonesia tidaklah cukup untuk mendorong aspek substantif dari kesejahteraan. Hasilnya, sebagai contoh meski suatu daerah memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat besar.
Namun kesejahteraan masih menjadi ilusi. Dalam Report Celios menemukan bahwa di daerah yang APBD cukup besar karena ditopang oleh sektor ekstraktif justru yang terjadi ialah akses kepada kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan komunikasi malah semakin sulit. Hal ini terjadi sebab demokrasi tidak dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan. Demokrasi hanya dimaknai sempit sebagai proses elektoral, padahal kesejahteraan dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan.
Kesejahteraan Dalam Kontestasi Rezim
Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang dilaksanakan secara serentak harus menjadi bahan refleksi kita semua. Dengan mengutip hasil survei dari Indikator Politik Indonesia tentang ekspektasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun yang akan datang menempatkan masalah ekonomi sebagai masalah utama seperti mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok 30.4%, dan menyediakan lapangan pekerjaan 18.9%.
Kedua masalah tersebut merupakan masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Kemudian disusul mengurangi kemiskinan 10.3%, pemberantasan korupsi 7.6%, memajukan sektor pertanian 7.5% dan pembangunan/perbaikan infrastruktur 6.6%. Persoalan lain lebih rendah menjadi perhatian warga.
Studi Indikator tersebut mengindikasikan bahwa sektor ekonomi menjadi pokok perhatian dan permasalahan yang sangat mendesak saat ini. Disatu sisi disaat yang bersamaan, pemilu 2024 menjadi catatan sejarah kelam mengenai praktik anti demokrasi dimana seseorang bisa mencalonkan diri dan terpilih dengan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu lewat mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
Kejadian seperti itu sebenarnya merupakan pola atau skema yang digambarkan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblaat dalam merangkai suatu skenario mengenai bagaimana tanda-tanda demokrasi itu mati. Namun demikian isu tersebut sepertinya kurang berdampak, dalam suatu istilah yang digunakan Burhanuddin Muhtadi isu-isu seperti etika, pembegalan konstitusi dan dinasti politik ibarat badai dalam secangkir kopi. Isu demikian tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, hal ini ditengarai karena menguatnya kepentingan ekonomi bagi pemilih di Pemilihan Umum tahun 2024 sehingga demokrasi substansial kadangkala terabaikan dengan narasi populis kesejahteraan.
Oleh karena itu penting untuk menyadarkan semua pihak bahwa proses penguatan demokrasi akan senantiasa berhasil apabila kemudian diikuti oleh perkembangan ekonomi yang semakin membaik pula. Kedepan publik perlu dididik bahwa hanya dalam proses demokrasi yang sehat, ekonomi yang baik pula dapat tercapai dan begitu pula sebaliknya. Semakin rezim pemerintahan bergerak kearah non demokratik, ada kecenderungan semakin terpuruk pula kondisi ekonomi.
Program kesejahteraan yang kerap kali dijual dalam kontestasi rezim, harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral serta sebagai sumpah atau janji jabatan untuk menghadirkan kesejahteraan substantif lewat produk kebijakan yang berbasis pada hukum progresif.
Mahasiswa Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM
2 Pengikut

Benarkah Demokrasi Sudah Menghantarkan Kita Kepada Kesejahteraan?
Selasa, 3 Desember 2024 18:46 WIB
Dari Trump ke Prabowo
Sabtu, 23 November 2024 07:23 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 97
97 0
0